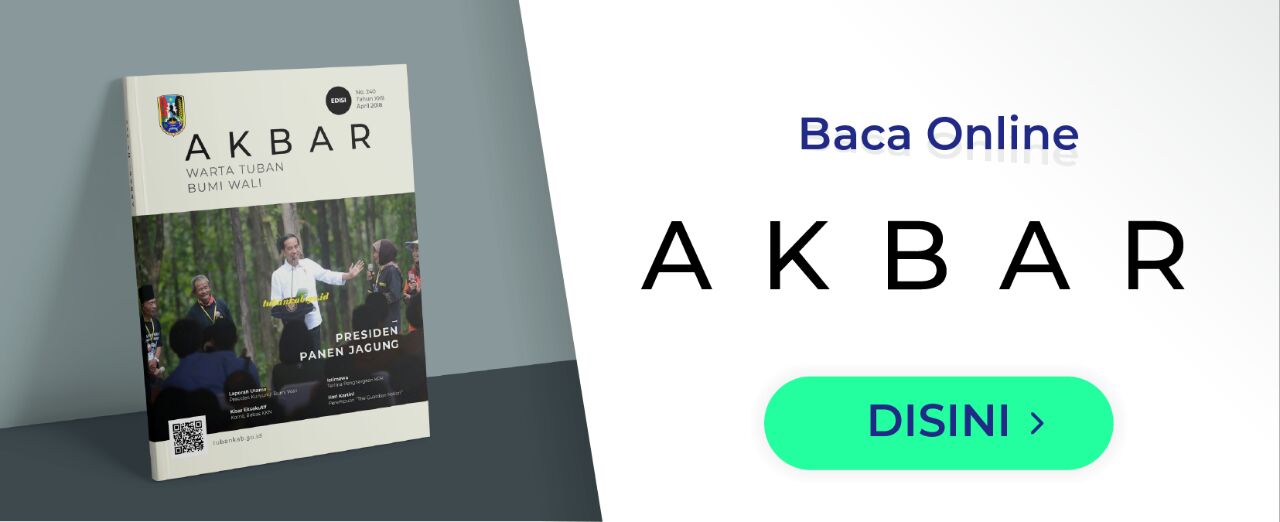M. Ngalimun, Saksi Sejarah Kelam Bicara tentang Patriotisme dan Keikhlasan Berjuang
- 29 August 2023 13:04
- Heri S
- Umum,
- 1854
Tubankab - Pada 7 Mei 1945, Jerman yang menyerah kepada sekutu menjadi pertanda akan berakhirnya perang dunia kedua. Imbasnya, Jepang yang kala itu merupakan sekutu dari Jerman mendapatkan tekanan dari Eropa untuk segera mengakhiri perang di kawasan asia pasifik. Namun, Jepang menolak, hingga peristiwa besar terjadi, di mana Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 Agustus 1945. Peristiwa itu menjadi pertanda tahap akhir perang dunia kedua.
Dalam kemelut tersebut, 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Namun, hal tersebut tak serta merta membebaskan bangsa Indonesia menikmati kemerdekaan seutuhnya. Pertempuran kembali pecah pada November 1945, di mana tentara Inggris-India, yang merupakan sekutu Belanda, menyulut amarah para pemuda Indonesia, karena telah menyebarkan ancaman agar Indonesia segera mengembalikan senjata rampasan perang.
Dalam kisah di atas, reporter Diskominfo-SP berhasil berhasil menemui M. Ngalimun, salah satu pejuang kemerdekaan asal Kabupaten Tuban untuk menggali lebih jauh peristiwa heroik tersebut. Mantan pejuang yang kini tinggal di Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, ini merupakan salah satu saksi sejarah kelam, yang harus kembali dialami oleh bangsa Indonesia, meskipun telah memproklamasikan kemerdekaannya.
Ngalimun yang saat ini telah berusia 95 tahun menceritakan, tahun 1945, meskipun Indonesia telah merdeka, kata “merdeka” dan Indonesia belum familiar di telinganya. Begitu pun masyarakat Tuban. Namun, pagi itu, 10 November 1945, melalui siaran radio yang terdengar di tengah Kota Tuban, Ngalimun yang baru berusia 16 tahun mendengarkan pidato Bung Tomo yang berapi-api penuh dengan semangat. Ia juga baru pertama kali mendengar kata bahwa Indonesia tidak hanya Tuban, namun terdiri dari berbagai suku dan kepulauan.
Dalam pidato Bung Tomo, alih-alih menyerah kepada sekutu, Bung Tomo mengajak seluruh rakyat Indonesia termasuk para pemuda dari seluruh daerah, untuk bersatu mengangkat senjata. Pidato tersebut berhasil membakar rasa nasionalisme rakyat dan pemuda Indonesia, termasuk Ngalimun untuk pergi berperang mempertahankan kemerdekaan .
“Merdeka atau Mati”, semboyan yang selalu menjadi amunisi semangat para pejuang kala itu. “Saya masih mengingat sampai sekarang, bagaimana dada ini bergetar untuk mantap membela negara bersama pemuda lainnya,” cerita Ngalimun.
Setelah mendapatkan dorongan semangat dari pidato Bung Tomo, serta nasihat dari para kiai bahwa membela bangsa dan negara adalah jihad. Tanpa pikir panjang, tahun 1946, Ngalimun memantapkan diri untuk ikut berjuang dan mendaftar menjadi seorang perajurit di Laskar Hisbullah.
Memang, dalam kurun waktu 1943 hingga 1945, hampir seluruh pondok pesantren membentuk laskar-laskar pejuang, termasuk Laskar Hisbullah yang mulai didirikan di akhir pendudukan Jepang tahun 1945.
Pembentukan Laskar Hisbullah atas usulan KH. Wahid Hasyim, yang disiapkan untuk mempertahankan pulau Jawa dari penjajah.
Para santri ini dibekali pengetahuan militer, dan mengikuti pelatihan di Cibarusa Bogor, dipimpin langsung oleh KH. Wachid Hasyim dan KH. Zainal Arifin . Para santri ini mendapatkan materi baris berbaris, bongkar pasang senjata, pembuatan senjata peledak, pembekalan agama dan motivasi jihad. 500 lebih santri disebar di seluruh Jawa Timur, dan mereka ditugaskan untuk membuat cabang- cabang hisbullah di daerah masing-masing, hingga terkumpullah 50 ribu Tentara Hisbullah di seluruh Indonesia.
Ngalimun pun bergabung dalam Laskar Hisbullah cabang Tuban-Bojonegoro, seperti yang lain. Ia juga mendapatkan pendidikan militer di bawah komando Imam Nur Faqih. Beruntung, saat ia bergabung di tahun 1946, persenjataan Laskar Hisbullah Tuban paling lengkap di antara Laskar Hisbullah lain di Jawa Timur.
Ia menceritakan, atas bantuan para nelayan dari Kelurahan Kingking, yang mengetahui adanya senjata Jepang yang dibuang di kawasan Pantai Boom, Tentara Hisbullah Tuban mendapatkan banyak senjata. Ratusan senjata saat Jepang meninggalkan Indonesia tahun 1945 dibuang di wilayah Pantai Boom. Senjata ringan berkaliber 9 milimeter, senjata laras panjang yang jumlahnya ratusan, senjata karaben, serta mortir itu, diberikan oleh nelayan Kingking kepada para Tentara Hisbullah. sebagai rasa terima kasih, melalui bantuan Masyumi, setiap senjata dihargai beras sebesar 5 kg, dan 10 kg untuk yang berukuran besar.
“Waktu itu masyarakat kelaparan, dan beras adalah barang yang sangat mahal kala itu. Meskipun mereka melakukan dengan senang hati, tapi dari kala itu Bapak-bapak Masyumi memberi imbalan beras,” kenang Ngalimun.
Berkat itu, Tentara Hisbullah Tuban terkenal yang paling gagah. Bagaimana tidak, di tengah kekacauan yang serba kekurangan, mereka mendapatkan senjata masing-masing satu. Sebelumnya, Ngalimun mengaku satu senjata harus digunakan untuk 3 orang. “Malah di Bojonegoro 1 senjata untuk 10 prajurit,” kenangnya.
Untuk peluru, para pejuang juga harus mengais peluru bekas peninggalan Jepang dan Belanda yang masih tersisa. Kesehariannya ia habiskan dengan berlatih senjata bersama dengan perajurit lainnya, sambil menjaga markas di wilayah Kebumen, Kelurahan Ronggomulyo.
Tibalah Desember tahun 1946, ia ditugaskan di wilayah Cermai, untuk menjaga pertahanan daerah Surabaya barat di bawah Batalion Brigadir Ronggolawe. Dari utara terdapat batalion Sunaryadi, dan sebelah kanan batalion Jarot, memperkuat pertahanan Surabaya dari agresi militer Belanda.
Ngalimun mengisahkan salah satu pertempuran yang ia alami. Tahun 1947, saat bulan Suci Ramadan, pertempuran kembali terjadi di daerah Cermai. Kala itu, belanda berusaha untuk mengambil alih Cermai dari Bumi Pertiwi. Hujan peluru serta martir terjadi hampir di seluruh wilayah Surabaya. Saat itu, dengan persenjataan yang kalah jauh dari milik Belanda yang telah memiliki persenjataan modern, Ngalimun bersama pejuang lainnya harus bertahan dengan senjata sederhana dengan isi peluru hanya 10 butir.
Meskipun dalam pertempuran tersebut para pejuang berhasil mempertahankan wilayah Cermai, 3 orang rekan Ngalimun dari batalion Brigadir Ronggolawe harus gugur. Mereka adalah Rasipan dan Sarif. Jasadnya pun dibawa pulang ke Tuban untuk dikebumikan. Berbeda dengan Baidowi, yang tidak diketahui keberadaanya hingga saat ini. “Dia dibawa belanda, jasadnya tidak ditemukan,” kata Ngalimun.
Akhir 1948, Ngalimun pindah ke batalion militer Babat untuk menghalau Belanda, agar tidak masuk ke wilayah Tuban- Babat-Bojonegoro. Dalam misi tersebut, saat ia tiba, Belanda sudah berhasil masuk ke wilayah babat.
Ia kemudian bergeser ke wilayah Bojonegoro, atas perintah Letnan Kolonel Sudirman, untuk mempertahankan sisi selatan Bengawan Solo. Di sana, ia bersama pejuang lain menuju Desa Sugihwaras Bojonegoro, masuk pada kesatuan barisan di bawah pimpinan Letnan Sun’an.
Saat perang gerilya, setiap malam, Ngalimun mengendap-ngendap menuju ke markas Belanda untuk mengusir mereka. “Jangan sampai Belanda tidur pulas di Ibu Pertiwi. Kita usik mereka,” katanya tegas.
Ia juga menceritakan, dalam masa perang gerilya, Ngalimun merasakan ikatan batin antara rakyat dengan para pejuang. Di mana para ibu selalu menyiapkan makanan untuk para prajurit saat bergerilya, dan bapak-bapak yang siap menjaga mereka bersembunyi saat melakukan pengintaian. Meskipun keadaan serba kekurangan, rakyat selalu bersama para pejuang, bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
“Yang berjuang tidak hanya kita para perajurit, namun ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di desa, Masyaallah, tidak pernah lelah membantu kita menyiapkan makan dan tempat istirahat,” kenangnya dengan penuh haru.
Saat ini, di usia senjanya, ia habiskan dengan membaca buku, mendekatkan diri kepada Tuhan , dan menemani sang istri menjalani hari.
Memori tentang perjuangan masih melekat. Tak sedikit pun terkikis oleh waktu. Rasa cintanya terhadap negara juga masih sama, menjalar ke seluruh aliran darah dan sukma.
78 tahun sudah bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Tak lagi kita rasakan hujan peluru di siang bolong, teriakan seorang anak yang kehilangan ibunya akibat perang, rasa cemas seorang istri di malam hari menunggu suami pulang dari medan pertempuran, atau rasa mencekam penduduk desa, ketika operasi militer penjajah menggunakan tank dengan persenjataan lengkap, lewat di depan rumah.
Kemerdekaan yang kini telah dirasakan adalah buah dari kerja keras, pengorbanan, tetesan keringat, darah dan air mata dari para pejuang bangsa. Mereka meninggalkan orangtua, istri dan anak, untuk pergi melawan penjajah tanpa mengenal kata menyerah.
“Bersyukur saat ini akses pendidikan gampang, dan banyak mencetak sarjana. Gelar itu harus digunakan untuk membangun bangsa, menjadi SDM berkualitas. Yang terpenting, rasa nasionalisme harus tetap ada dalam diri kita. Karena dengan nasionalisme, kerukunan akan terus terjalin. Siapapun engkau, apapun agamamu, apapun suku dan etnismu tetaplah tanamkan jiwa nasionalisme dalam diri.
“Kemajuan yang ada saat ini jangan menjadikan kita puas. Masih ada kurang di sana dan di sini. Ini adalah tugas generasi penerus untuk memenuhi kekurangan tersebut. Demi tegaknya Republik Indonesia sejahtera, yang makmur, dan berdasarkan Pancasila,” tutupnya. (nurul jamilah/hei)